Generasi Zaman Now yang Tak Kenal Sastra – Sastrawan muda yang bernama Faisal Oddang bercerita tentang peserta seminar yang tidak familiar ketika ia menyebut sekira duapuluhan nama sastrawan pilih tanding.
Kata Oddang, ada satu peserta mengaku akrab dengan nama Tere Liye, tapi ketika Oddang bertanya judul buku milik Tere Liye mana yang pernah ia baca, mahasiswa itu pun terbata-bata mengaku bahwa ia sejujurnya hanya menyukai tulisan-tulisan di kiriman status Facebook akun Tere Liye. http://nahjbayarea.com/
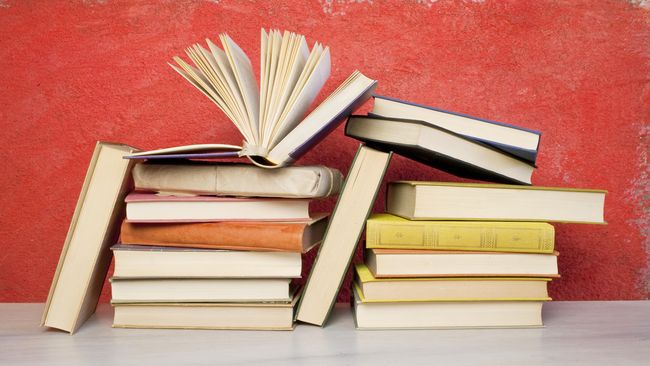
Cerita Oddang itu harusnya begitu menyentil dalam situasi dunia sastra yang sejak dulu sibuk berdebat soal politik sastra hingga kanon-kanon sastra. Di level praktis, politik sastra dan kanon sastra yang membicarakan sastra sebagai sebuah karya dengan beragam teknik penyajian, eksperimen gaya bahasa, juga misi muluk yang dipercaya akan membawa dampak adiluhung buat dunia itu tidak punya suara. Perkara yang sampai kepada orang biasa adalah selalu segala sesuatu yang bersifat mainstream alias budaya massa. Saat ini, budaya massa mewujud dalam rupa-rupa status dan topik terkini yang viral dalam sebuah jejaring dan spesifik pada hari tertentu.
Saya pernah mengalami kejadian serupa Oddang sewaktu mengisi sebuah acara pelatihan menulis di sebuah kampus. Kabar kurang menyenangkannya, mahasiswa yang sedang belajar menulis ketika itu adalah calon-calon guru. Mereka adalah sarjana pendidikan yang sudah mengabdi selama satu tahun pula di daerah terluar dan terpencil di Indonesia, tetapi ketika saya menyebut beberapa nama sastrawan Indonesia berikut judul buku mereka, persis seperti Oddang, tidak ada sahutan. Bahkan, tampak jelas pada air muka mereka semacam ekspresi “tidak terhubung” sama sekali dengan topik yang dibicarakan.
Saya tidak piawai membicarakan sastra, tetapi saya pembaca yang percaya bahwa karya sastra yang lekat dengan istilah dulce et utile itu adalah salah satu jenis harapan yang membantu kita untuk membedakan hal baik dan buruk, juga mana hal indah dan semrawut. Jangan bilang-bilang pada mereka yang saleh sebab berani-beraninya menyerupakan sastra dengan peran agama, ya!
Ada cerita yang lebih mengerikan lagi. Pada sekitar tahun 2014, sebuah kampus cukup ternama mengadakan seminar nasional bahasa dengan memanelkan tiga pemantik diskusi: Seno Gumira Ajidarma, Triyanto Triwikromo, dan satu orang lagi adalah seorang doktor bidang sastra pengajar di kampus terkait. Seno selalu menjadi sastrawan rendah hati dalam semua forum. Dia mengatakan bahwa dia jarang menulis kritik sastra, bukan karena tidak ada yang perlu dikritik, tetapi sebab ia selalu merasa kekurangan waktu membaca karya-karya sastra terbaik yang terbit dari seluruh dunia.
“Saya merasa sudah ngebut membaca. Tapi tetap saja, karya terbaik yang terbit dari seluruh dunia lebih cepat dari kecepatan membaca saya. Kadang saya sampai nggak bisa ngikutin dinamika yang ada di Indonesia sendiri.”
Tahun itu, Triyanto Triwikromo baru saja menerbitkan novel Surga Sungsang. Triyanto juga memaparkan sedikit jurnal ilmiahnya yang mengulas wacana perempuan dalam karya-karya Sastrawangi. Triyanto sama seperti Seno, tidak hanya mengajar di kelas, tetapi masih terus menyimak perkembangan sastra kontemporer di berbagai media selain menghasilkan karya-karya bagus yang selalu disegani dan dibicarakan banyak orang.
Yang membuat saya gagal paham adalah justru pengakuan Pak Dosen yang konon presentasi makalah dalam seminar itu biar lekas jadi profesor. Ia kagok menyebut satu judul cerpen Seno, dan percaya diri menyatakan tidak mengikuti perkembangan sastra Indonesia sejak belasan tahun lalu. Jangan tanya apakah beliau ini menghasilkan karya di media massa atau tidak, lha wong mengikuti perkembangan bacaan-bacaan terbaru saja nggak, lho! Wah, padahal ketika itu saya datang seminar sebagai pembaca snob yang membawa buku Senja dan Cinta yang Berdarah, kumpulan cerpen Seno setebal bantal yang ketika itu baru saja terbit. Usai acara, saya pun minta tanda tangan dan berfoto dengan pencipta tokoh Sukab, juga Alina yang suka dikirimi sepotong senja itu. Maklum, namanya juga pembaca snob!
Setelah itu saya nggak berani membayangkan materi apa yang diajarkan oleh dosen-dosen sastra yang tidak lagi membaca sejak belasan tahun lalu di kelas. Saya ikut terbayang materi pelajaran bahasa Indonesia semasa sekolah yang diproduksi oleh rezim Orde Baru. Rezim yang membuat pengetahuan sastra beberapa kurun generasi menjadi begitu terbatas. Belajar bahasa di masa sekolah adalah mempelajari seperangkat aturan kebahasaan, tidak berbeda dengan rumus matematika atau ilmu alam yang rumit dan jarang mengesankan. Guru bahasa juga jarang menyebut (apalagi membicarakan) karya-karya kanon. Perjumpaan saya dengan karya ngepop seperti teenlit di perpustakaan tentu saja karena cover yang atraktif dan cerita yang dekat dengan emosi khas anak remaja.
Jadi, kembali lagi, seandainya saya masih menjadi mahasiswa baru yang ditanya Oddang dalam seminar di atas, saya pun tidak berbeda dengan peserta kebanyakan. Aduh, sedihnya!
Lho, tapi kan sudah lama kita tahu kalau sastra ini nggak penting-penting amat buat kehidupan di Indonesia. Kebutuhan manusia yang utama dan pertama tentu saja adalah makanan. Setelahnya, selain hunian, pakaian adalah rekreasi juga hiburan. Dua terakhir itu tergolong mewah buat warga biasa Indonesia. Rekreasi lebih sering diartikan sebagai mengunjungi tempat-tempat wisata yang ramai untuk melepaskan kepenatan setelah lelah bekerja. Hiburan, bisa didapatkan dari televisi dan gawai, yang kini berisi sumber-sumber hoax, mulai dari grup Whatsapp keluarga hingga grup Whatsapp alumni.
Baru-baru ini, muncul perspektif baru di dunia pariwisata alias rekreasi. Konon, tren AirBnB (marketplace airbed and breakfast asal Amerika Serikat) membuat siapa saja bisa menyewakan hunian, rumah bahkan sekadar satu kamar sebagai tempat penginapan bagi wisatawan domestik maupun turis asing. Tren itu mengakibatkan kegiatan piknik tidak lagi dimaknai mengunjungi kawasan-kawasan wisata yang terkenal, tetapi kini piknik yang sesungguhnya adalah mengenal penduduk lokal, berbaur dan tinggal bersama mereka. Tak heran, didukung dengan promosi mandiri via Instagram, banyak desa biasa kini mempromosikan diri sebagai desa wisata dengan tawaran paket kunjungan yang beragam, mulai dari paket budaya hingga paket wisata pertanian.
Cara pandang pendekatan sastra di sekolah punya banyak jalan untuk berbenah. Kita tidak akan membicarakan sastra kanon-kanonan atau mana yang lebih nyastra atau tidak. Kita hanya ingin memperkenalkan sastra sebagai dirinya sendiri, yakni sebuah usaha estetis bahasa yang ingin memberitahukan kita banyak hal. Kita bukan akan belajar sastra, tetapi rekreasi bersama sastra.